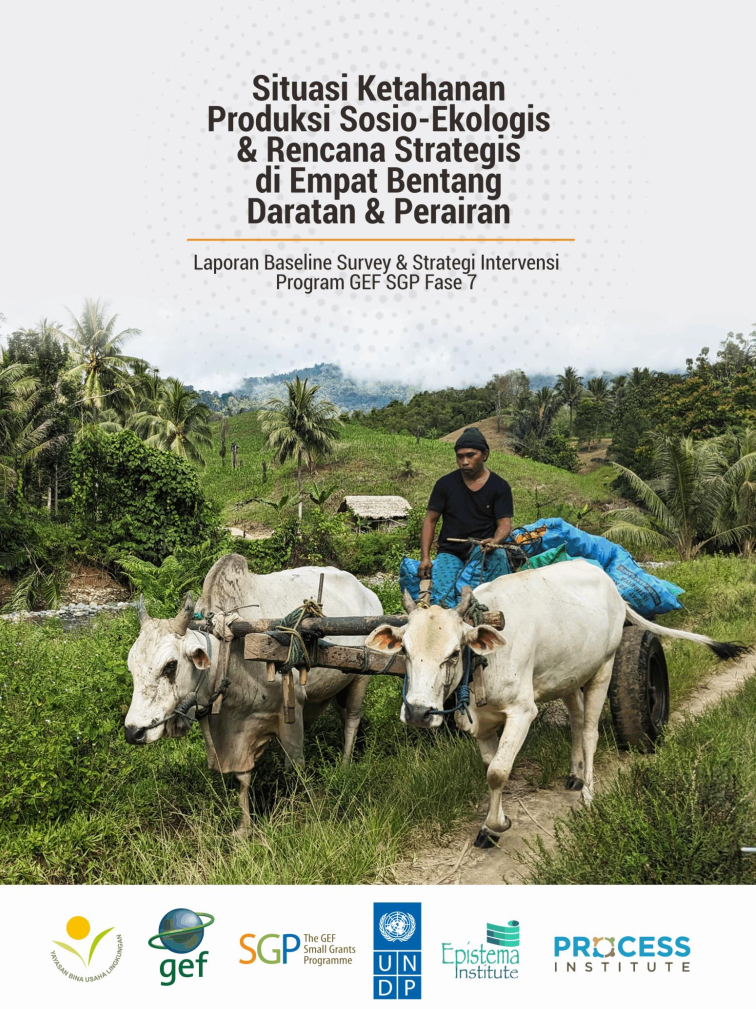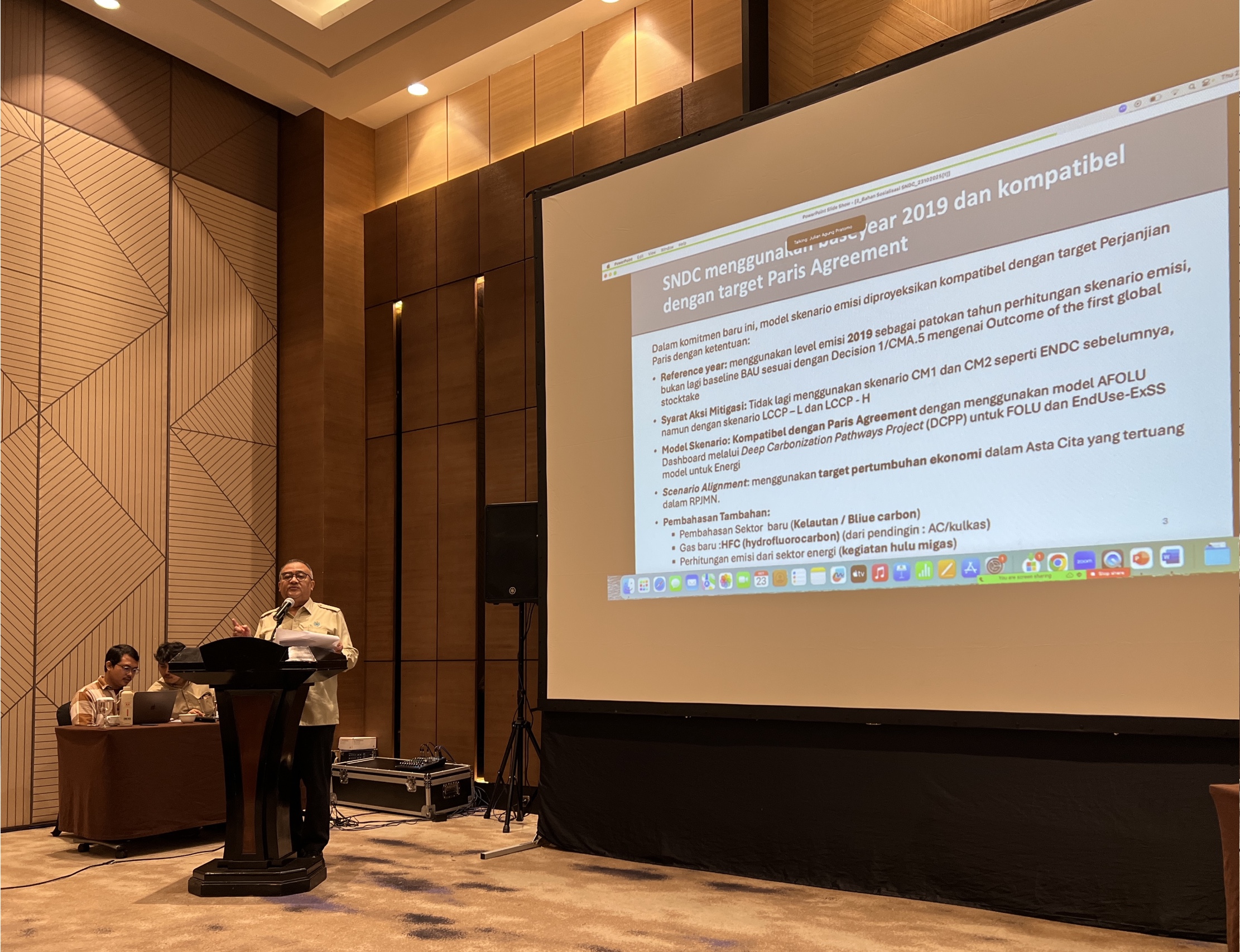Rencana pembangunan berskala besar di Indonesia, seringkali dibungkus dengan dalih meningkatkan ketahanan pangan, energi atau pariwisata. Meskipun terdengar mulia, sejarah kegagalan proyek ambisius di Indonesia memberikan alasan untuk mempertanyakan inisiatif yang mengorbankan lingkungan dan kaum marjinal.
Pada tahun 2024, Yayasan PIKUL bersama para mitra di Indonesia Timur telah melakukan riset kolaboratif untuk menggali persoalan yang dihadapi masyarakat akibat dari proyek pembangunan dan perubahan iklim. Melalui empat seri diskusi publik, terungkap kepentingan ekonomi berskala besar kerap mengesampingkan hak-hak serta kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Sejarah mencatat, berbagai mega proyek di Indonesia, baik itu food estate, pariwisata super premium, maupun industri ekstraktif, selalu berujung pada malapetaka. Di berbagai lokasi studi di Indonesia Timur, riset menunjukkan kebijakan dan proyek pembangunan, yang diklaim sebagai solusi adaptasi, justru menciptakan maladaptasi, yaitu tindakan yang memperparah kerentanan atau menimbulkan masalah baru.
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh EKORA NTT di Desa Ja’o Du’a, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende, proyek percetakan sawah yang digadang-gadang sebagai lumbung pangan justru berujung gagal. Kebijakan pemerintah dalam proyek ini telah menggeser sistem pertanian dan cara pandang masyarakat terhadap pangan. Sistem pertanian yang sebelumnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan kini berorientasi ekonomi.
Dinas Pertanian Kabupaten Ende melalui Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Pertanian, J. Djoni Aba, SP menjelaskan, masuknya proyek percetakan sawah di Desa Jeo Dua dan delapan desa lainnya pada tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
“Kita menentukan lokasi karena ada CPCL (calon petani calon lokasi). Setelah disetujui baru bisa dilaksanakan. Intinya ada sumber air, potensi lahan, dan ketersediaan masyarakat.”
Pada tahun yang sama, berdasarkan data evaluasi program cetak sawah Kabupaten Ende tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Ende, proyek ini dilaksanakan di enam desa yang tersebar di enam kecamatan. Desa Koanara di Kecamatan Kelimutu memiliki target cetak sawah seluas 12 hektar, Desa Je’o Du’a di Kecamatan Detukeli seluas 42 hektar, Desa Woloau di Kecamatan Maurole seluas 12 hektar, Desa Tou Barat di Kecamatan Kota Baru seluas 23 hektare, Desa Wolomage di Kecamatan Detusoko seluas 80 hektar, dan Desa Wolojita di Kecamatan Wolojita seluas 36 hektare.
Anehnya, dalam program percetakan sawah ini, aparat TNI dilibatkan secara aktif. Keterlibatan ini merujuk pada Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI Angkatan Darat dan Kementerian Pertanian RI yang ditandatangani pada 8 Januari 2015, dengan tujuan mendukung pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan, melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kegiatan pencetakan sawah jelas tidak termasuk dalam mandat tersebut.
Dalam diskusi dengan Gabriel Gara Beni, SP, Kepala Bidang Pertanian dan Agrikultur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, pihaknya mengatakan hanya mengikuti instruksi dari atasan. Ia juga menyebut bahwa keterlibatan TNI mungkin dipilih karena dianggap mampu bergerak cepat di lapangan.
“Kami hanya mengikuti perintah dari pusat saja. Bukan berarti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak ada wewenang. Kami hanya mengikuti saja. Mungkin alasannya karena TNI dapat bergerak cepat” ujar Gabriel dalam Diskusi Publik DIseminasi Hasil Seri IV.
Lahan hutan dibuka, ekosistem rusak, dan konflik antar keluarga adat muncul. Dari 145 jenis pangan lokal yang dulu menjamin kedaulatan pangan, masyarakat kini hanya bergantung pada beras, yang bahkan harus didatangkan dari luar. Proyek ini tidak hanya mengikis keberagaman pangan, tetapi juga mengganggu struktur sosial dan ekonomi warga setempat. Keterlibatan militer pun dipertanyakan karena tidak efektif menjawab kebutuhan petani.
Sementara itu, di Labuan Bajo dan Mandalika, proyek pariwisata strategis nasional berubah menjadi mesin akumulasi modal yang hanya menguntungkan segelintir elit. Privatisasi pesisir dan laut membatasi akses tradisional nelayan, yang akhirnya dipaksa beralih ke sektor wisata dengan pendapatan yang tidak menentu dan persaingan ketat dengan pendatang.
Di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), hasil riset Gema Alam menunjukkan proyek Pembangunan Strategis Nasional (PSN) telah membawa dampak besar bagi masyarakat dan lingkungan. Mandalika ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan destinasi pariwisata internasional. Pembangunan infrastruktur, termasuk sirkuit balap internasional, disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Investasi senilai 17,7 triliun rupiah telah dikucurkan, dengan target penciptaan 40.000 lapangan kerja. Pemerintah mengklaim program ini berhasil mentransformasi Mandalika dari wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi menjadi kawasan yang dinilai progresif.
Namun, dibalik narasi pembangunan tersebut, terdapat konsekuensi serius. Proyek PSN telah menyebabkan hilangnya dusun, hutan bakau, pasar pelelangan ikan, serta berbagai sumber daya penting yang menjadi tumpuan hidup masyarakat. Pantai dan laut, yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan tradisional, kini telah dialihfungsikan menjadi kawasan pariwisata dan infrastruktur global. Perubahan ini berdampak langsung pada kondisi lingkungan, mulai dari penurunan kualitas air, hilangnya habitat alami, hingga kerusakan ekosistem pesisir.
Pembangunan infrastruktur besar di Mandalika juga bertepatan dengan peningkatan kejadian iklim ekstrim. Proyek pembangunan di Mandalika dicirikan sebagai maladaptasi karena bukannya mengurangi kerentanan, justru menciptakan krisis baru dan memperparah kerentanan yang sudah ada. Hal ini termasuk peningkatan emisi gas rumah kaca, membebankan kelompok rentan, biaya tinggi, hilangnya kemampuan adaptasi, dan penyempitan ruang hidup masyarakat. Pembangunan ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang antara pemerintah, investor dengan masyarakat lokal.
Pariwisata super prioritas juga membawa dampak besar bagi Labuan Bajo. Berdasarkan riset Floresa, penetapan Labuan Bajo sebagai salah satu dari “10 Bali Baru” dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) telah mendorong transformasi wilayah ini menjadi destinasi super-premium yang dibentuk oleh logika akumulasi modal. Di balik panggung pertumbuhan ekonomi, kebijakan ini lebih banyak menguntungkan investor besar dan segelintir elit lokal, sementara masyarakat setempat hanya kebagian “tetesan kecil” dari keuntungan yang dihasilkan.
Investasi masif di kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya telah merusak habitat komodo, memprivatisasi ruang laut dan pesisir, serta menggusur ruang hidup masyarakat. Aktivitas tradisional seperti memancing dan ritual adat tergeser oleh pembangunan hotel, tanggul, dan infrastruktur wisata. Pembukaan 400 hektare hutan Bowosie dan proyek PLTP di Waesano untuk mendukung pariwisata memperdalam kerusakan ekologis. Di laut, menjamurnya kapal wisata dengan lampu dan musik keras mengganggu biota, sementara nelayan kecil kesulitan melaut karena ruang gerak mereka direbut oleh industri wisata. Banyak dari mereka terpaksa beralih menjadi pekerja pariwisata berupah rendah, di tengah cuaca ekstrem yang menyulitkan penangkapan ikan dan biaya operasional yang semakin tinggi.
Ironisnya, pemerintah daerah justru mendorong transformasi profesi nelayan ke sektor pariwisata, mengabaikan nilai ekonomi dan ekologis dari praktik tradisional yang selama ini menopang keberlanjutan hidup masyarakat. Kebijakan yang diterapkan bersifat top-down, tidak responsif terhadap krisis iklim, dan minim partisipasi bermakna. Alih-alih membangun ketahanan, proyek ini menciptakan maladaptasi struktural di mana pembangunan memperparah kerentanan, mempersempit ruang hidup, dan menciptakan krisis baru bagi masyarakat lokal.
Industri ekstraktif pun tidak ketinggalan menyumbang kerusakan. Di Halmahera, Kolaka, dan Sikka, ekspansi tambang nikel dan geothermal yang diklaim sebagai bagian dari transisi energi justru menimbulkan pencemaran, abrasi, dan kerusakan laut. Bahkan, di Sikka, warga menolak proyek panas bumi mengalami intimidasi. Nama baru “ekstraktivisme hijau” ternyata tidak mengubah watak lamanya: eksploitatif dan eksklusif.
Krisis iklim memperparah situasi. Nelayan kesulitan memprediksi cuaca, hasil tangkapan menurun drastis, dan kelangkaan air bersih menjadi masalah nyata di banyak wilayah. Perempuan, sebagai pengelola rumah tangga dan sumber pangan, menanggung beban ganda. Di Kupang, badai Seroja menghancurkan usaha garam tradisional dan memaksa warga kehilangan sumber penghidupan.
Akar dari semua ini adalah ketidakadilan struktural dan kebijakan yang tersentralisasi. Keputusan dibuat secara top-down, minim partisipasi masyarakat adat, dan sering berpihak pada kepentingan korporasi. Pemerintah mengukur keberhasilan dari pertumbuhan ekonomi, sementara masyarakat melihat dari ketercukupan kebutuhan dasar. Ketimpangan kekuasaan ini juga memperkuat kolusi dan korupsi dalam implementasi proyek-proyek besar.
Tumpang tindih antara pembangunan berskala besar dan krisis iklim di Indonesia Timur tidak bisa dilepaskan dari realitas ketimpangan struktural yang dijelaskan oleh teori stratifikasi sosial Max Weber. Weber menyatakan bahwa ketimpangan sosial tidak hanya terjadi karena perbedaan ekonomi (wealth), tetapi juga karena distribusi yang tidak adil atas status sosial (prestige) dan kekuasaan (power). Dalam konteks ini, pembangunan seperti food estate, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan proyek pariwisata super-premium cenderung dikuasai oleh segelintir elite ekonomi dan politik yang memiliki akses terhadap modal, legitimasi negara, dan pengaruh kebijakan. Sementara itu, masyarakat termasuk petani, nelayan, dan perempuan, tidak hanya kehilangan sumber penghidupan mereka, tetapi juga mengalami degradasi status sosial ketika praktik tradisional mereka dianggap ketinggalan zaman dan tidak produktif dalam logika pembangunan modern.
Kekuasaan politik terpusat di tangan negara dan investor, meminggirkan partisipasi warga lokal dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa proyek pembangunan dan narasi transisi energi yang diklaim untuk kesejahteraan bersama, pada kenyataannya memperkuat relasi kuasa yang timpang dan melanggengkan eksklusi sosial-ekologis
Di tengah semua ini, perempuan muncul sebagai garda depan dalam adaptasi dan ketahanan. Mereka yang paling terdampak, tetapi juga yang paling aktif merespons. Namun, partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan tetap terbatas. Bahkan, banyak kebijakan tidak mengakui peran perempuan sebagai nelayan atau petani, sehingga menghambat akses mereka terhadap perlindungan dan dukungan negara. Analisis ini juga selaras dengan perspektif ekofeminisme, yang memandang bahwa dominasi terhadap alam dan penindasan terhadap perempuan berakar dari sistem patriarkal dan kapitalistik yang sama. Ekofeminisme menyoroti bagaimana perempuan, terutama di komunitas adat dan pedesaan, memiliki relasi yang erat dengan alam sebagai penyedia pangan, air, dan obat-obatan. Ketika alam dirusak demi kepentingan ekonomi elite, perempuan juga mengalami kerentanan ganda, baik secara ekologis maupun sosial.
Perempuan juga memainkan peran penting sebagai agen perubahan, menjaga pengetahuan lokal, mengelola sumber daya secara berkelanjutan, dan memimpin gerakan komunitas. Sayangnya, dominasi narasi pembangunan maskulin yang mengagungkan teknologi, modal, dan efisiensi ekonomi seringkali mengabaikan suara dan pengalaman perempuan. Maka, keadilan iklim tidak dapat tercapai tanpa mengakui dan memperkuat posisi perempuan sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan lingkungan.
Kita membutuhkan arah baru. Adaptasi yang adil bukan soal proyek-proyek besar, tapi keberpihakan pada keragaman lokal. Secara khusus di NTT, pemetaan pangan lokal yang dilakukan oleh PIKUL pada tahun 2013 di berbagai pulau dan kabupaten menemukan setidaknya 36 jenis sumber pangan lokal. Sumber pangan ini mencakup serealia (seperti jagung, padi, sorgum, jali, jewawut), umbi-umbian (keladi, talas, singkong, ganyong, ubi jalar, dan umbi-umbian hutan), serta berbagai jenis kacang-kacangan. Keragaman ini memiliki potensi besar untuk mendukung swasembada pangan berbasis daerah dan memenuhi kebutuhan gizi rumah tangga, apabila dikembangkan secara konsisten dan tidak digerus oleh logika pembangunan monokultur yang mengabaikan kekayaan benih lokal.
Pembangunan yang membebaskan harus berpijak pada keadilan iklim, evaluasi kebijakan yang merugikan, penguatan partisipasi kelompok rentan terutama perempuan, pengembangan ekonomi regeneratif yang menempatkan kesejahteraan manusia dan alam di atas pertumbuhan semata, serta kolaborasi lintas sektor yang memprioritaskan suara dari akar rumput.
Retorika besar tentang ketahanan pangan, energi, dan pariwisata hanya akan menjadi ilusi jika terus melanggengkan eksploitasi dan marginalisasi. Di tengah krisis ganda antara proyek pembangunan dan krisis iklim, saatnya kita membalik arah. Masyarakat lokal bukan objek, melainkan subjek pembangunan. Inilah momen untuk membangun masa depan yang adil, berkelanjutan, dan berakar kuat pada kekuatan komunitas.