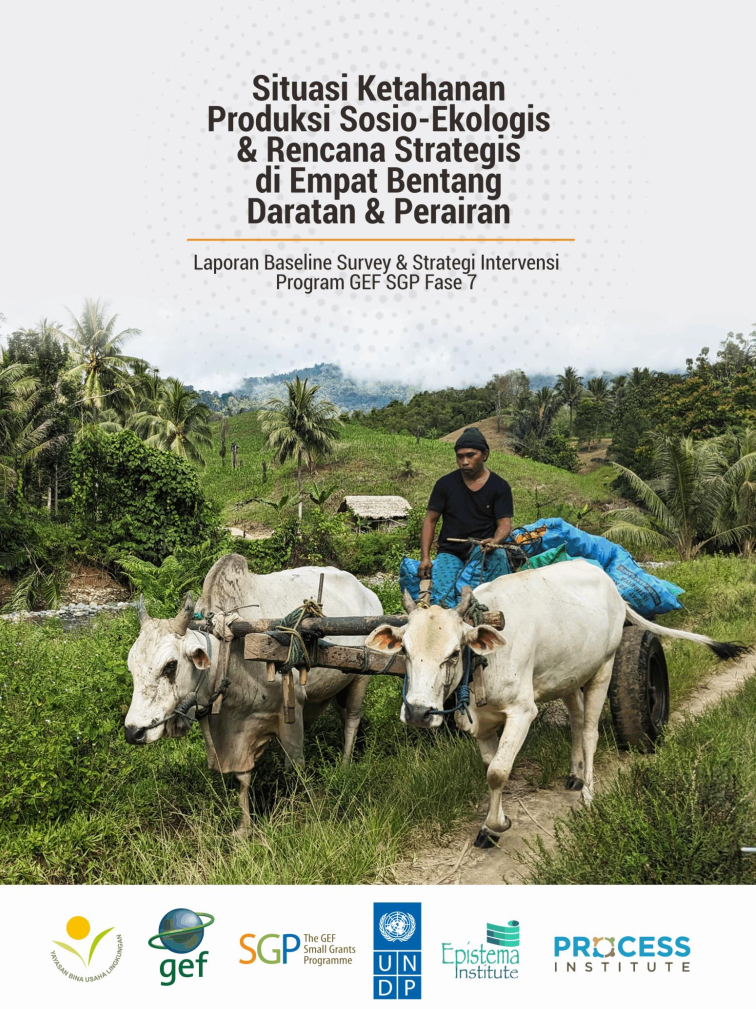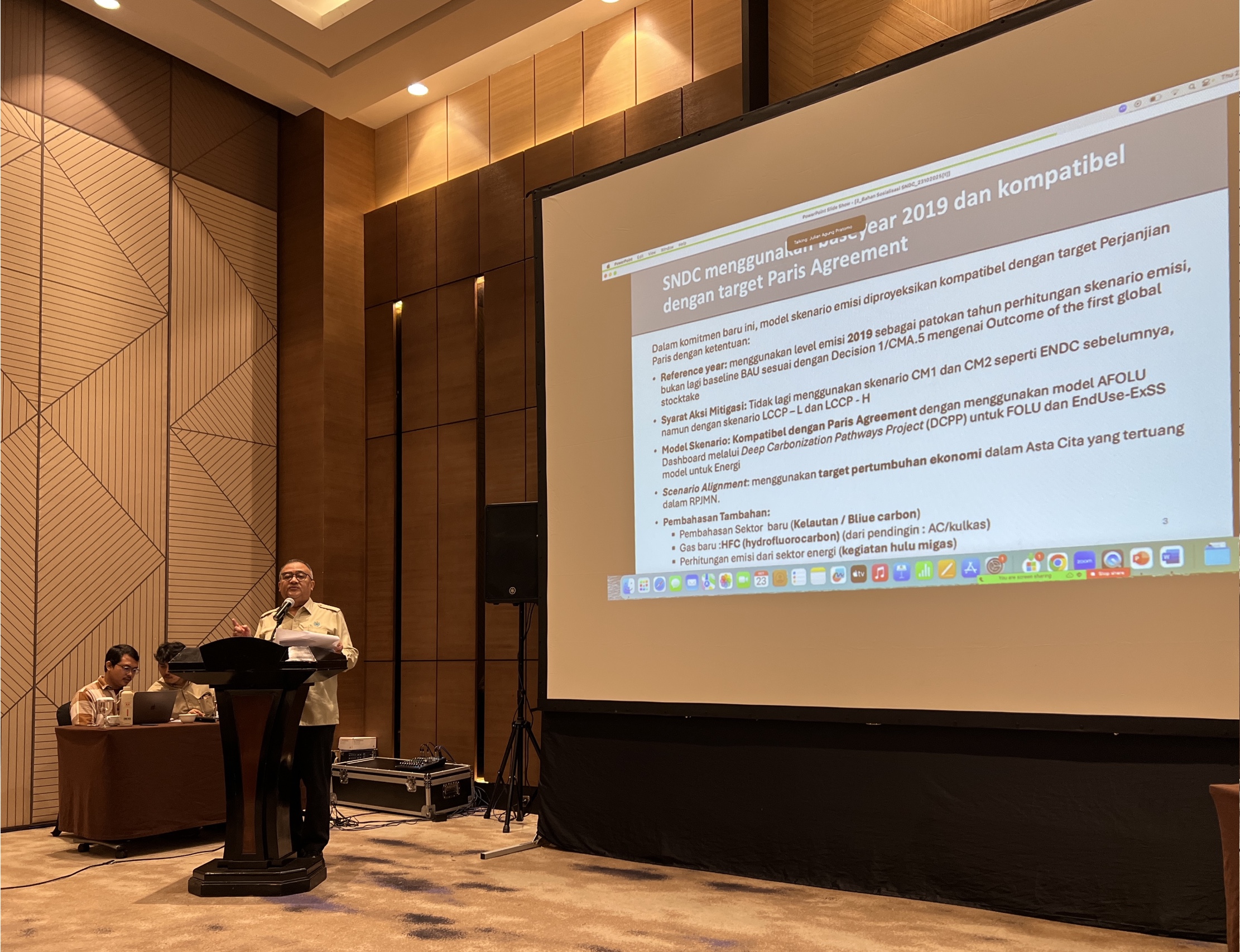“Kita di NTT ini su biasa hidup susah. Prinsip kami diperhatikan pemerintah pusat ya syukur, tidak diperhatikan juga tidak apa-apa. Sudah terbiasa hidup apa adanya” komentar salah seorang warganet di tiktok.
Gelombang protes nasional menolak kenaikan tunjangan DPR/RI pada akhir Agustus 2025 mengguncang banyak kota di Indonesia. Namun, di Nusa Tenggara Timur (NTT) responnya berbeda. Banyak masyarakat justru menganggap demo itu sia-sia. “Lebih baik kerja daripada demo,” begitu komentar yang sering terdengar. Sikap ini tampak seperti budaya pasrah, tetapi jika ditelusuri lebih dalam, ia adalah produk dari kemiskinan, pendidikan yang terbatas, dan kebijakan nasional yang seringkali meminggirkan rakyat. Apatisme masyarakat NTT bukan sekadar persoalan malas berpikir atau tidak peduli. Ia adalah mekanisme bertahan hidup di tengah realitas keras. Dalam teori Pierre Bourdieu, ini bisa disebut symbolic domination: sistem membuat orang percaya bahwa kegagalan adalah kesalahan mereka sendiri, bukan akibat struktur yang timpang. Noam Chomsky menyebutnya sebagai penjara pikiran, di mana masyarakat diyakinkan bahwa keadaan tidak bisa diubah (Herman & Chomsky, 1988 – Manufacturing Consent).
Kemiskinan dan Hilangnya Ruang Kritis
NTT konsisten berada di lima provinsi termiskin di Indonesia, dengan angka kemiskinan 20,3% (BPS, Maret 2024). Pendidikan pun masih timpang, angka putus sekolah tinggi, dan lulusan sarjana tidak menjamin pekerjaan layak. Amartya Sen menegaskan bahwa kemiskinan adalah capability deprivation, bukan sekadar kurang pendapatan, melainkan hilangnya kemampuan mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan bermartabat. Kondisi ini membuat ruang kritis masyarakat menyempit akibatnya demo dianggap buang-buang waktu sementara bertahan hidup dipandang lebih penting.
Kebijakan Nasional: Jauh tapi Dekat
Ketika sejumlah mahasiswa menggelar demo di depan Polda NTT pada 28 Agustus 2025 lalu, sebagian beranggapan bahwa “ Demo di sini salah sasaran. Pi demo di Jakarta sana”. Padahal, setiap kebijakan nasional mulai dari alokasi APBN, subsidi pangan, harga BBM, hingga program sosial langsung menyentuh dapur rumah tangga, lahan petani, dan kantong pedagang kecil di kota. Kenaikan tunjangan DPR/RI adalah simbol betapa timpangnya prioritas negara. Elit politik memperkaya diri, sementara rakyat harus berjuang dengan ongkos hidup yang terus naik.
Proyek Strategis Nasional (PSN) di Labuan Bajo misalnya. Demi pariwisata super premium, warga lokal harus berhadapan dengan konsesi bisnis yang mengorbankan akses mereka pada ruang hidup. UNESCO bahkan mengkritik pemerintah Indonesia karena model pariwisata super-premium di Komodo berpotensi merusak ekologi dan memarginalkan masyarakat lokal (Floresa.co).
Kebijakan ini diperkuat dengan UU Cipta Kerja, misalnya pasal 23 yang menyatakan bahwa hanya proyek “berdampak penting” yang wajib AMDAL, mempermudah bisnis tanpa kajian mendalam. Selain itu, pasal 121 yang memberi kemudahan investasi, tapi tidak memperkuat perlindungan buruh. Sementara itu, UU Minerba (UU No. 2 Tahun 2025) menegaskan kewenangan penuh pemerintah pusat dalam izin tambang (Pasal 5 & 6), membuat masyarakat daerah kehilangan suara dalam mengelola sumber daya mereka.
Buruh Kota Kupang: Hidup Berat, Upah Murah
Di Kupang, kisah buruh sering terdengar pahit. Rita, penjaga toko, bekerja tanpa kontrak jelas dengan gaji hanya Rp800 ribu hingga Rp1,5 juta. Windi harus berdiri 12 jam sehari tanpa libur, tapi upahnya tak lebih dari Rp800 ribu. Bahkan Neno, remaja berusia 14 tahun, ikut turun tangan bekerja demi menambah penghasilan keluarga. Bagi lulusan sarjana seperti Jeny dan Kesya, ijazah tak menjamin apa-apa—mereka akhirnya banting setir berjualan online sekadar bisa bertahan hidup. Padahal, pemerintah sudah menetapkan UMP NTT 2025 sebesar Rp2,3 juta, dengan UMK Kota Kupang Rp2,39 juta. Angka itu hanya jadi catatan di atas kertas, karena mayoritas buruh informal tak pernah merasakan upah layak. UU Cipta Kerja justru memperparah keadaan dengan sistem kontrak pendek dan outsourcing, sementara pengawasan ketenagakerjaan di NTT nyaris tak berjalan. Pelanggaran dibiarkan, dan buruh dibiarkan sendirian.
Ketidakadilan inilah yang perlahan menumbuhkan apatisme. Kalimat seperti “lebih baik kerja daripada demo” bukan lahir dari kemalasan, melainkan dari keyakinan pahit bahwa melawan tidak akan mengubah keadaan. Sosiolog Mark Rank menyebut kemiskinan seperti permainan kursi musik: orang menjadi miskin bukan karena malas atau bodoh, melainkan karena kursi yang tersedia terlalu sedikit dibanding jumlah orang yang membutuhkannya.
Apatisme di NTT lahir dari kemiskinan yang menahun, pendidikan yang timpang, hingga kebijakan nasional yang menyingkirkan rakyat. Diam memang bisa menyelamatkan hari ini, tapi ia juga melanggengkan ketidakadilan untuk esok. Selama kita pasrah, harga kebutuhan tetap naik, gaji tetap rendah, dan anak-anak tetap sulit sekolah, sementara elit makin nyaman di kursinya. Sikap pasrah ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sengaja dipelihara.
“Besong tu harusnya berterima kasih karena pemerintah masih kasih bansos.” pernyataan seperti ini nyaring ada dimana-mana. Ini membuktikan bahwa rakyat seringkali digiring untuk percaya bahwa bansos, subsidi, atau program bantuan lain adalah hadiah yang patut disyukuri, padahal konstitusi jelas mewajibkan negara menjamin pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial bagi seluruh warga.
Narasi “terima kasih pada pemerintah” yang terus diproduksi justru menumpulkan kekritisan, membuat rakyat merasa utang budi, dan menjadikan ketidakadilan tampak wajar. Pertanyaannya, maukah kita terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sengaja dipelihara negara? Apatisme bukan pilihan netral. Ia adalah keberpihakan pada elit yang terus mengeruk keuntungan dari keringat rakyat kecil. Diam hanyalah memberi jalan bagi penguasa untuk makin menutup telinga dari suara di Timur.
Jika kita terus pasrah, kita hanya akan menjadi penonton dalam permainan politik yang memperkaya segelintir orang di Jakarta, sementara rakyat NTT tetap dihitung sekadar angka. Satu-satunya cara keluar dari kebuntuan ini adalah melawan dengan suara, dengan keberanian, dengan keyakinan bahwa kita berhak atas kursi yang sama dalam ruang kehidupan berbangsa. Pendidikan kritis harus diperkuat agar orang – orang muda tidak lagi terbuai narasi pasrah dan mampu membaca ketimpangan dengan jelas. Komunitas lokal, serikat buruh, dan organisasi masyarakat sipil harus menjadi benteng perlawanan, ruang kolektif untuk menekan pemerintah agar benar-benar menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Bersatu dan menuntut hak secara konsisten bukan lagi pilihan tapi keharusan. Hanya dengan aksi nyata dan tekanan yang terus-menerus, lingkaran apatisme bisa dipatahkan, dan ketidakadilan yang menahun bisa digerakkan menuju perubahan yang konkret dan tidak bisa diabaikan lagi. Sebab tanpa perlawanan dengan daya pikir kritis yang tinggi kita akan selamanya dibiarkan duduk di lantai, sementara kursi tetap dikuasai oleh elit/EG.
Sumber :
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Persentase Penduduk Miskin Maret 2024. Jakarta: BPS.
- Floresa.co (2025, 1 Agustus). Mengapa Konsesi Bisnis di Taman Nasional Komodo Sangat Berbahaya dan Harus Dihentikan. Diakses dari https://floresa.co/
- Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York: Pantheon Books.
- Rank, M. R. (2004). One Nation, Underprivileged: Why American Poverty Affects Us All. Oxford: Oxford University Press.
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. New York: Knopf.
- Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press.
- Project Multatuli. (2025, 15 Agustus). Kesaksian Generasi Cemas di NTT: Upah Murah, Jam Kerja Panjang, Sarjana Susah Cari Kerja. Diakses dari https://projectmultatuli.org/
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).