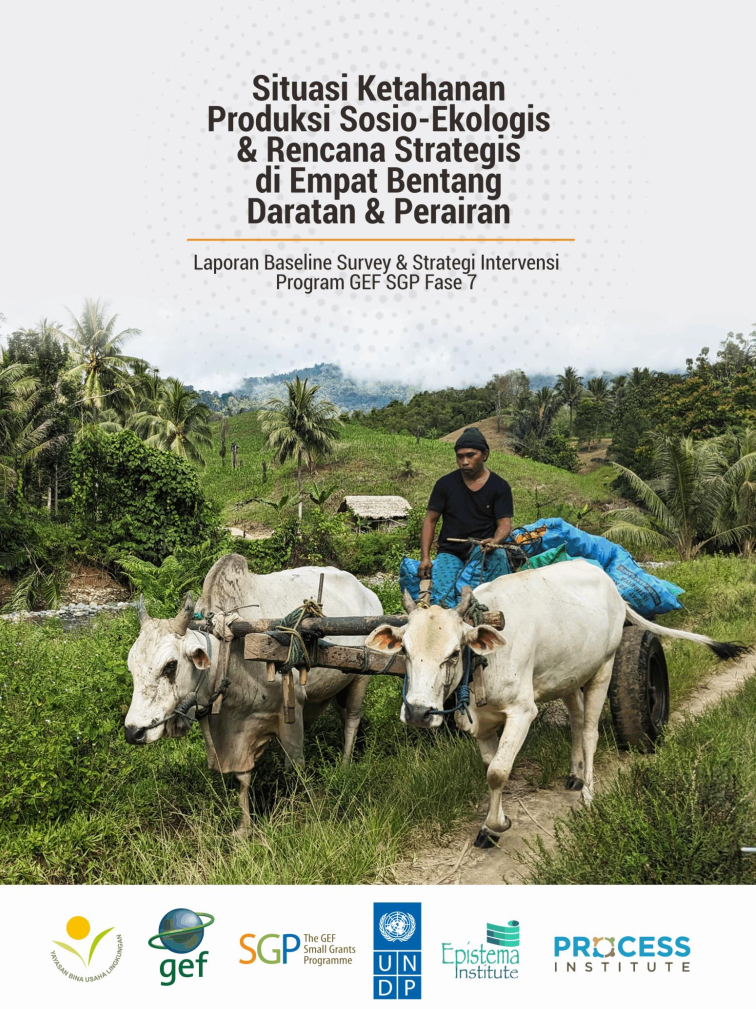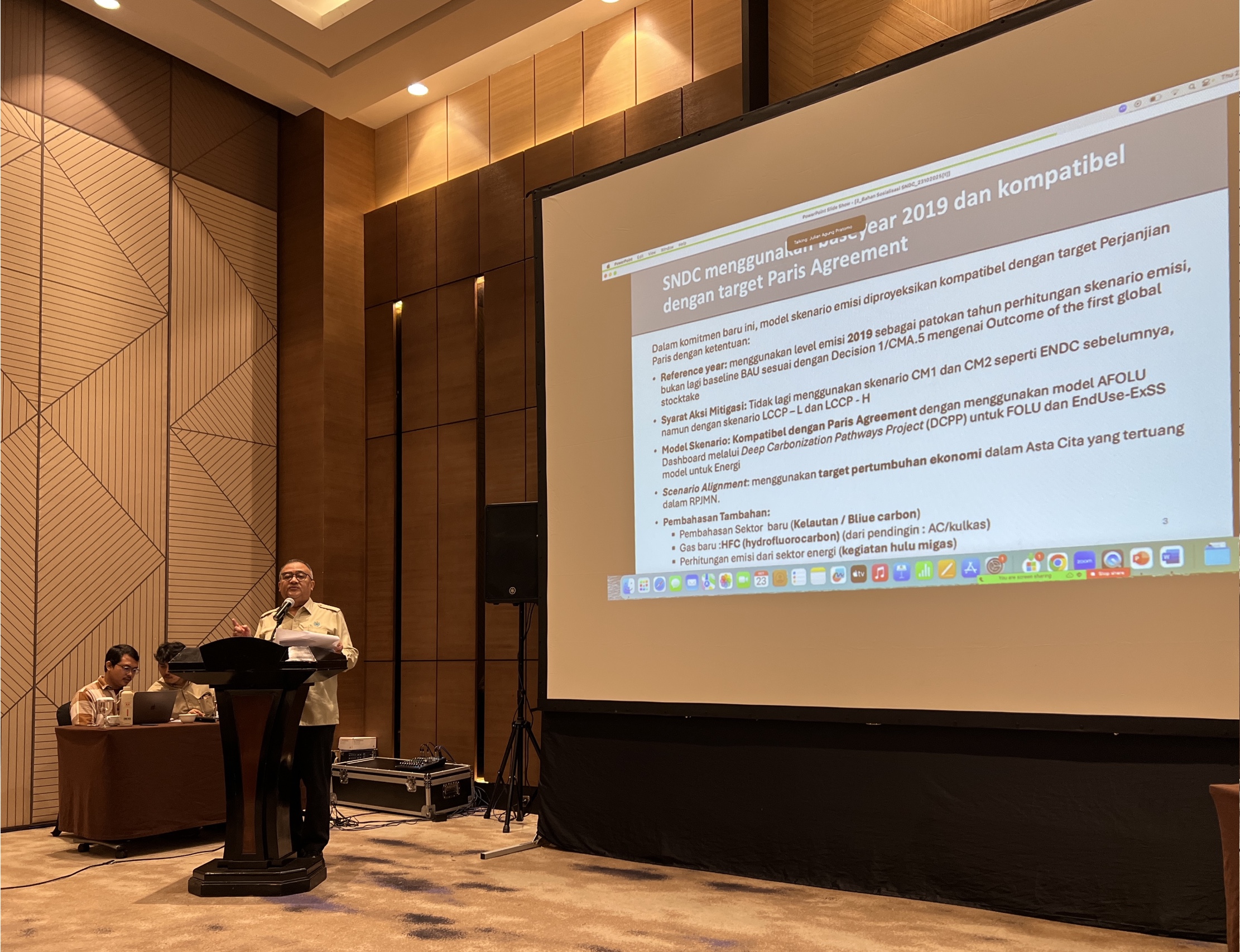DISPARITAS ANTAR DAERAH
Isu ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia masih serius meski desentralisasi telah berjalan sekitar 26 tahun. Padahal desentralisasi seharusnya meratakan pembangunan dengan memberi keleluasaan bagi daerah merancang program sesuai konteks lokal (Mu’minah & Tjenreng, 2025). Banyak studi mencatat jurang antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Penelitian oleh Sayadi(2020) misalnya yang menunjukkan realisasi PAD di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Tengah jauh lebih baik daripada seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Atau penelitian oleh Syaifudin et al., (2024), di mana ia menemukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita DKI Jakarta 10 kali lipat PDRB per kapita Maluku, dan 5 kali lipat PDRB per kapita Papua, di mana DKI Jakarta mencatat PDRB per kapita tertinggi sebesar Rp 298,35 juta per tahun, atau rata-rata sekitar Rp 24,86 juta per bulan, sedangkan Provinsi Papua mencatat PDRB per kapita Rp 59,384 juta per tahun, yaitu hanya sekitar 20% dari angka Jakarta.
Ketimpangan tersebut sesungguhnya terjadi karena keseragaman logika pembangunan yang diterapkan di beberapa provinsi. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam laporan World Bank bahwa terdapat pendekatan one-size fits all dalam desentralisasi fiskal di Indonesia, padahal setiap provinsi dan kabupaten menghadapi tantangan yang berbeda. Pendanaan yang seragam ini lebih sering menguntungkan daerah-daerah yang sudah memiliki kapasitas birokrasi dan infrastruktur memadai, sementara daerah tertinggal kian sulit mengejar ketertinggalan karena tidak ada ruang kebijakan yang disesuaikan konteks lokal (Diop et al., 2014). Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi desentralisasi fiskal serta pembangunan daerah yang lebih disesuaikan pada konteks serta kapasitas daerah.
DESENTRALISASI ASIMETRIS SEBATAS AKOMODASI POLITIK
Strategi tersebut sebenarnya telah diupayakan lewat desentralisasi asimetris yang bahkan logikanya telah diisyaratkan dalam UUD 1945 pada Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B. Desentralisasi asimetris sendiri sederhanya adalah pemberian kewenangan khusus yang berbeda dengan daerah-daerah lain kepada suatu daerah tertentu. Namun, penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia lebih didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat “reaktif’ ketimbang pada pengelolaan hubungan pusat dan daerah (Kurniadi, 2012). Desentralisasi asimetris untuk Aceh dan Papua misalnya, diterapkan untuk menetralisir perlawanan separatisme. Untuk wilayah lain seperti Yogyakarta juga terlihat pola yang serupa, di mana desentralisasi asimetris muncul sebagai bentuk penghormatan negara terhadap hak historis dan asal-usul pemerintahan tradisional di Yogyakarta yang juga merupakan respon atas deklarasi Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengintegrasikan daerah Yogyakarta ke dalam NKRI (Siregar & Fatimah, 2023).
Kasus-kasus desentralisasi asimetris di atas menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia masih terbatas pada akomodasi cultural diversity (Purwosantoso et al., 2011) atau bahkan masih terbatas pada akomodasi politik dan ideological diversity seperti pada kasus Aceh dan Papua untuk menjawab ketidakadilan (grievance) distribusi sumber daya dan keinginan (greed) aktor lokal untuk mengakses sumber daya di daerah mereka (Tadjoeddin, 2007). Penerapan desentralisasi asimetris yang demikian pun berimplikasi pada hasil pembangunan daerah yang belum maksimal, termasuk dirasakan oleh daerah-daerah yang telah mengalami desentralisasi asimetris (khususnya Aceh dan Papua) seperti yang terlihat pada data-data yang disajikan sebelumnya.
GEOGRAPHICAL DIVERSITY SEBAGAI ELEMEN DESENTRALISASI ASIMETRIS
Penulis ingin memperluas diskusi mengenai desentralisasi asimetris dengan mencoba melihat hal tersebut bukan sebagai instrumen akomodasi politik ataupun cultural dan ideological diversity, tetapi juga untuk merespon geographical diversity (keberagaman geografis) yang ada di Indonesia. Salah satunya ialah isu daerah kepulauan yang telah dicoba untuk dijawab melalui RUU Daerah Kepulauan. Provinsi-provinsi dengan bentuk geografis kepulauan (Kepri, Babel, NTB, NTT, Sulut, Sultra, Maluku & Malut) menghadapi masalah unik dan spesifik yang berbeda dengan wilayah daratan-daratan besar lain. Isu paling utama tentu saja berkaitan dengan konektivitas antar pulau yang mengintegrasikan kegiatan-kegiatan ekonomi antara pulau besar dan pulau kecil sehingga dapat menghindari keterisolasian.
Kendala transportasi antar pulau ini tidak hanya menyebabkan terhambatnya kemajuan ekonomi masyarakat lokal, akan tetapi juga mengakibatkan pelayanan publik (kesehatan & pendidikan) yang sangat minim di pulau-pulau kecil sehingga kesejahteraan sosial dan kualitas sumber daya manusia juga bermasalah (Puspitawati, 2020; Suawa, 2018). Selain itu, ketiadaan infrastruktur yang memadai serta ancaman iklim juga berkontribusi pada ketimpangan daerah antar wilayah kepulauan dan wilayah daratan.
Oleh karena itu, diperlukan suatu format hubungan pusat-daerah yang mampu menyelesaikan permasalahan unik tersebut. Kewenangan-kewenangan serta distribusi fiskal yang diserahkan ke provinsi kepulauan haruslah sensitif terhadap luas laut yang dominan di provinsi-provinsi tersebut. Mengutip dari policy brief oleh Purwidyasari (2025), desentralisasi asimetris terhadap wilayah kepulauan dapat dilihat dari tiga dimensi: kewenangan khusus, dana otonomi khusus dan kelembagaan khusus. Pemerintah provinsi diperlukan untuk memiliki kewenangan khusus dalam mengelola wilayah laut mereka, seperti dalam hal pembagian wilayah laut, perizinan, ekstraksitivisme dan transportasi. Dana otonomi khusus juga diperlukan untuk menutupi biaya pelayanan publik yang memperhatikan luas laut, jumlah serta jarak antar pulau. Selain itu, provinsi kepulauan juga harus memiliki lembaga-lembaga pemerintahan yang menyesuaikan pelayanan publik dengan kondisi geografis, contohnya seperti puskemas terapung.
DINAMIKA RUU DAERAH KEPULAUAN DAN URGENSINYA PADA KONTEKS NUSA TENGGARA TIMUR
Idealitas desentralisasi asimetris yang juga memperhitungkan keberagaman geografis dalam hal wilayah kepulauan telah dirumuskan dalam RUU Daerah Kepulauan yang diajukan Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan yang terdiri dari 8 provinsi kepulauan. Badan ini mendefinisikan daerah kepulauan sebagai daerah yang luas wilayah lautnya lebih besar dari wilayah daratan, penduduk yang relatif sedikit dan penyebaran yang tidak merata serta tersegregasi di antara pulau-pulau (Stefanus, 2011). Oleh sebab wilayah laut yang lebih luas tersebut, maka RUU ini mencoba untuk memfasilitasi pemerintah daerah dengan kewenangan serta hak-hak fiskal yang dapat mengelola wilayah laut tersebut yang sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat lokal sehari-hari. Beberapa kewenangan yang diatur dalam RUU ini setidaknya mencakup tujuh hal: Kewenangan pengelolaan ruang laut dan sumber daya laut, pengelolaan hubungan laut antar pulau, pengelolaan izin pertambangan energi dan sumber daya mineral, pengelolaan pendidikan tinggi (termasuk kurikulum diploma di bidang kelautan, perikanan dan keperawatan), pengelolaan kesehatan, perdagangan antar pulau dalam skala besar serta ketenagakerjaan.
RUU ini juga nantinya akan mengatur dana perimbangan. Selama ini, provinsi-provinsi kepulauan mendapat alokasi DAU yang kriterianya berdasarkan jumlah penduduk dan luas daratan. Hal ini tentu saja tidak adil bagi daerah-daerah kepulauan yang luas lautnya lebih besar daripada daratan sehingga menghadirkan tantangan tersendiri yang tidak tertutupi dengan dana perimbangan eksisting sekarang. RUU ini nantinya akan menetapkan Dana Transfer Khusus dengan memperhitungkan tingkat kemahalan yang mencerminkan karakteristik Daerah Kepulauan. Selain itu, RUU ini juga akan mengatur perencanaan pembangunan, sarana dan prasarana sesuai karakteristik kepulauan, perlindungan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan pulau kecil terluar serta partisipasi masyarakat.
NTT sebagai salah satu provinsi kepulauan memerlukan RUU ini karena dapat menyelesaikan ketimpangan antar pulau serta meningkatkan daya saing dengan daerah lain. NTT memiliki 1.192 dengan luas lautan 200.000 km², dan kondisi ini mendatangkan permasalahan uniknya tersendiri. Dilansir dari Mongabay.co.id, NTT rentan terkena dampak buruk perubahan iklim yang dapat mengakibatkan kehilangan pulau dan cuaca ekstrim. Selain itu, tidak adanya kerangka hukum yang pasti dalam mengelola laut membuat sumber daya laut sering dieksploitasi oleh masyarakat dengan cara-cara yang merusak alam seperti bom ikan. Potensi kelautan dan kepulauan di NTT juga tidak dapat dimaksimalkan tanpa RUU ini yang memberikan dana perimbangan untuk membangun infrastruktur yang mendukung pemanfaatan potensi-potensi tersebut. Selain perikanan, potensi lain yang dapat dimanfaatkan melalui RUU ini adalah energi terbarukan seperti arus laut, gelombang laut, panas laut, panas bumi, panas matahari dan angin.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dituntut untuk mengelola wilayahnya dengan pendekatan yang tidak seragam, tetapi kontekstual dan responsif terhadap keragaman geografis. RUU Daerah Kepulauan merupakan langkah penting dalam menginstitusionalisasi bentuk desentralisasi asimetris yang tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik atau historis, tetapi juga pada kebutuhan objektif wilayah kepulauan yang memiliki tantangan struktural tersendiri. Dengan pengakuan atas karakteristik geografis melalui pemberian kewenangan khusus, dana otonomi khusus, dan kelembagaan yang adaptif, RUU ini membuka peluang bagi daerah-daerah kepulauan seperti NTT untuk mengejar ketertinggalan, memperkuat kapasitas tata kelola, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengesahan RUU ini bukan hanya soal keadilan fiskal dan administratif, tetapi juga merupakan wujud nyata dari komitmen negara dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
REFERENSI
Diop, N., Fitrani, F., & Wai-Poi, M. G. (2014). Development Policy Review 2014 Indonesia: Avoiding The Trap Poverty (Nomor March).
Kurniadi, B. D. (2012). Desentralisasi asimetris di Indonesia. Dalam LAN Jatinangor (hal. 1–11).
Mu’minah, S., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Desentralisasi dan ketimpangan pembangunan antar daerah. Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 8(1), 342–351.
Purwidyasari, A. (2025). Policy Brief: Desentralisasi Asimetris untuk Provinsi Kepulauan (hal. 1–5). Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu Learning Center.
Purwosantoso, Pratikno, & Lay, C. (2011). Decentralized Governance. https://doi.org/10.2139/ssrn.3782214
Puspitawati, D. (2020). Pembangunan wilayah kepulauan berlandaskan poros maritim dalam perspektif negara kepulauan: Tantangan dan peluang perimbangan keuangan daerah. Bina Hukum Lingkungan, 4(2), 251. https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.107
Sayadi, M. H. (2020). Analisis perbandingan kinerja keuangan provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jurnal Ekonomi Modernisasi, 16(2), 96–104. https://doi.org/10.21067/jem.v16i2.4958
Siregar, R., & Fatimah, S. (2023). Dinamika desentralisasi asimetris di Daerah Istimewa Yogyakarta: Kajian kebijakan dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam, 19(2), 64–79.
Stefanus, K. Y. (2011). Daerah kepulauan sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Jurnal Dinamika Hukum, 11(1), 99–111. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.80
Suawa, J. J. (2018). Pembangunan daerah kepulauan untuk kesejahteraan rakyat. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 35(September), 11–18. http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/125
Syaifudin, R., Salman Alfarisi, M., Stephanie Regina Putri, G., Abdul Jabbar, M., Malik, A., & Zulfa, F. N. (2024). Determinan ketimpangan wilayah di Indonesia tahun 2012–2022: Pendekatan analisis panel dinamis. Journal of Business and Economics Research (JBE), 5(2), 129–137. https://doi.org/10.47065/jbe.v5i2.5143
Tadjoeddin, M. Z. (2007). A Future Resource Curse in Indonesia: The Political Economy of Natural Resources, Conflict and Development. CRISE Working Paper, 35, 1–43.