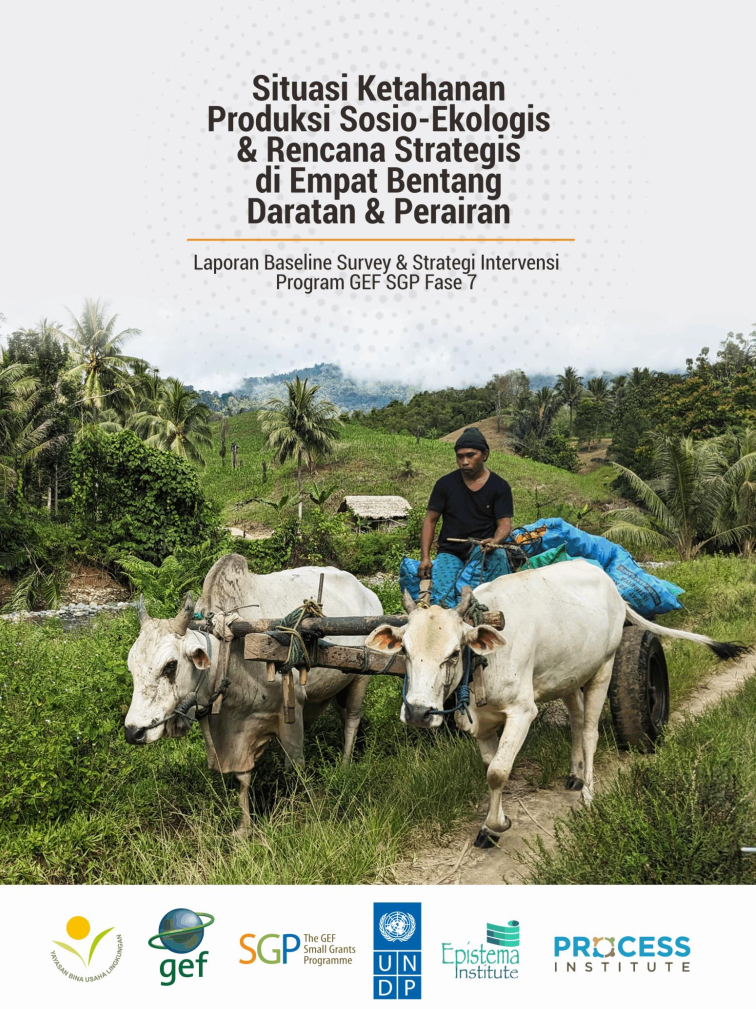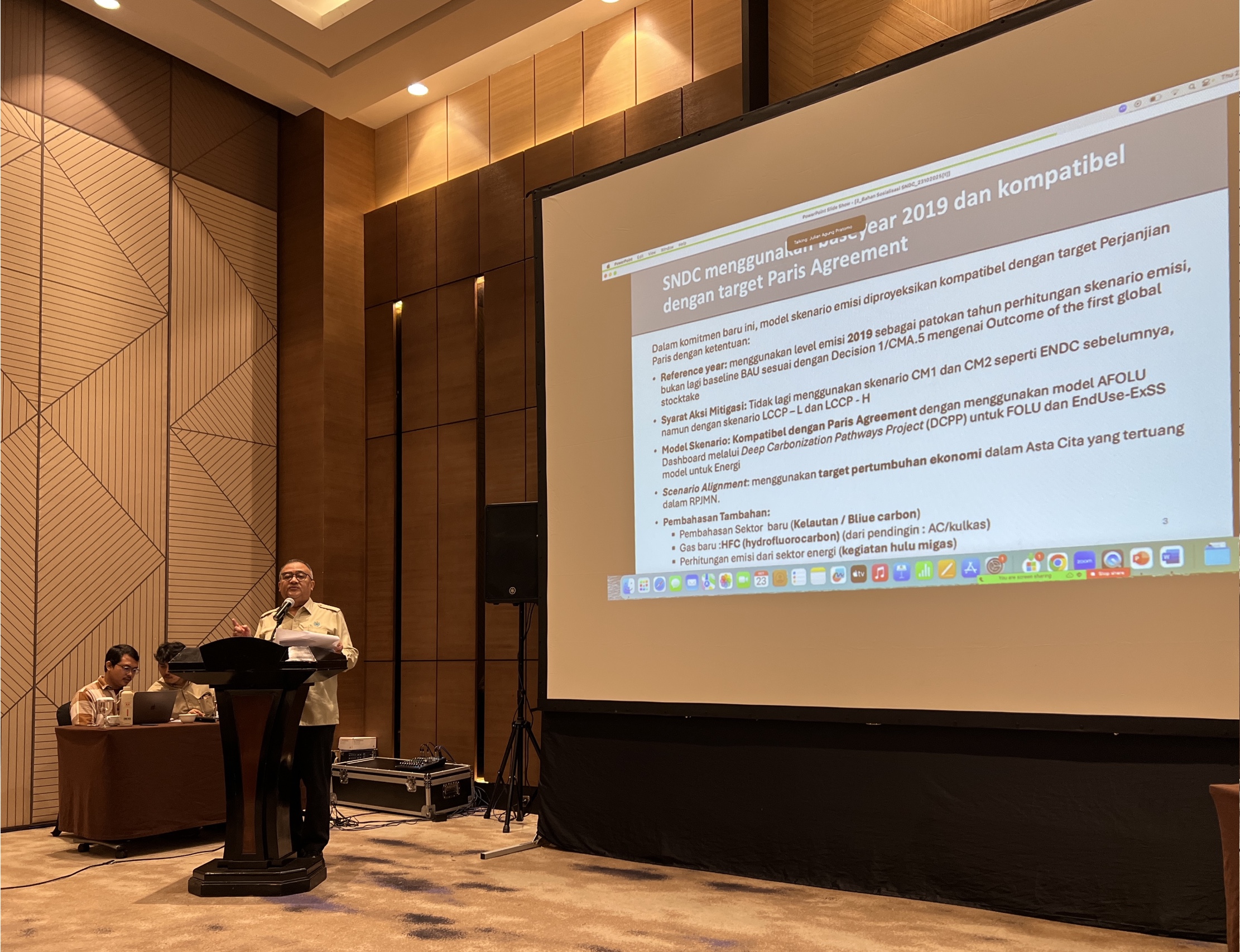Diskursus perubahan iklim dalam ruang-ruang akademik dan kebijakan seringkali terlalu jauh dari realitas konkret masyarakat di pinggiran. Bahasa teknokratik seperti “adaptasi” dan “resiliensi” berputar di ruang rapat, sementara di lapangan, masyarakat di daerah seperti Palue dan Magepanda hidup dengan musim yang kacau, tanah yang menganga retak, dan laut yang perlahan mencuri pemukiman mereka. Flores, dalam konteks ini, adalah cerminan telanjang dari apa yang disebut sebagai maladaptasi struktural.
Saya bukan berasal dari Flores. Saya tidak tumbuh bersama pohon-pohon lontar atau ladang-ladang jagung di Nusa Tenggara. Tapi saya belajar untuk peduli, karena krisis iklim menuntut kita untuk melampaui batas identitas geografis. Saya menulis ini bukan untuk mengklaim suara orang Flores, tetapi untuk mempertanyakan struktur yang membuat suara mereka tak kunjung terdengar. Dalam ruang publik kita, siapa yang layak didengar ketika tanahnya pecah dan airnya menghapus batas rumah?
Palue dan Magepanda memberi gambaran konkret tentang ketimpangan iklim. Di Palue, sebuah pulau vulkanik kecil di utara Flores, masyarakat hidup dalam percampuran antara ancaman bencana geologis dan iklim. Pola cuaca yang tak menentu menghancurkan siklus tanam yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di musim kemarau yang lebih panjang, tanah menjadi keras, merekah, dan mustahil digarap. Tanaman tak bisa tumbuh, ternak kehilangan pakan, dan tubuh para petani pun kering bersama bumi yang mereka gantungi. Ini bukan hanya soal pertanian, tapi soal kelelahan kolektif dari satu musim ke musim berikutnya yang tak kunjung berpihak.
Sementara itu, di Magepanda, wilayah pesisir Kabupaten Sikka, gelombang pasang dan abrasi perlahan-lahan menghapus garis pantai. Rumah-rumah yang dulunya berjarak belasan meter dari laut kini hanya selemparan batu dari ombak.
Di Magepanda pula, eksploitasi air tanah menjadi satu-satunya jalan keluar yang tersedia, sekaligus sumber persoalan baru. Saat curah hujan tidak lagi dapat diandalkan, warga menggantungkan hidup mereka pada sumur bor. Sebuah alat bertahan yang mahal, rapuh, dan jangka pendek. Setiap tetes yang diambil dari dalam bumi adalah isyarat krisis yang memburuk: keseimbangan hidrologis terganggu, lapisan tanah menurun, dan tanah yang dulunya subur kini keras, retak, dan kering jauh ke dalam.
Realitas ini tidak hanya ekologis, tetapi juga politis. Ketidakadilan iklim di Indonesia memperlihatkan wajah paling telanjang dari relasi kuasa antara pusat dan pinggiran, antara negara dan warga, antara pembangunan dan penghilangan. Proyek-proyek infrastruktur dan ekspansi pariwisata sering kali hadir tanpa konsultasi bermakna, seolah-olah tanah itu kosong, dan masyarakatnya diam. Negara justru mendesak “adaptasi” dari warga, ketika yang sebenarnya dibutuhkan adalah redistribusi perhatian, sumber daya, dan suara.
Namun, masyarakat tidak pasif. Di Magepanda, warga menanam kembali mangrove bukan semata demi konservasi, tapi untuk melindungi apa yang tersisa dari garis hidup mereka. Di Palue, pengetahuan lokal seperti membaca tanda-tanda cuaca dan merawat benih lokal kembali dijalankan. Ketahanan ini bukan produk intervensi negara, melainkan bentuk resistensi diam-diam yang lahir dari hubungan yang intim dan bersejarah antara manusia dan alamnya.
Dalam kerangka teoritis, situasi ini bisa dibaca melalui perspektif ekofeminisme dan dekolonisasi ekologi. Perempuan adalah kelompok yang paling terdampak dari rusaknya ekosistem. Karena mereka yang harus mencari air lebih jauh, merawat anak di tengah kelangkaan pangan, dan menjaga api di dapur yang makin sulit menyala. Tetapi pengetahuan mereka juga seringkali dikesampingkan dalam struktur ilmiah dan kebijakan yang bias patriarki dan pusat.
Tulisan ini adalah bentuk intervensi kecil dari seseorang yang memilih untuk tidak diam. Krisis iklim bukan hanya soal statistik suhu, tetapi soal siapa yang dipersilakan hidup dan siapa yang boleh dikorbankan. Ketika kebijakan iklim disusun tanpa mendengar Palue dan Magepanda, maka yang sedang dibangun bukan masa depan, melainkan pengulangan dari pola penghilangan.
Flores mengajarkan kita bahwa perubahan iklim adalah soal keadilan, bukan hanya ekosistem. Dan keadilan tidak pernah lahir dari diam atau netralitas. Kita perlu mendengar suara yang selama ini diabaikan, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka justru punya pengetahuan dan ketahanan yang telah melampaui banyak konferensi dan pernyataan global.
Kontributor Tulisan: Sherly Leneng