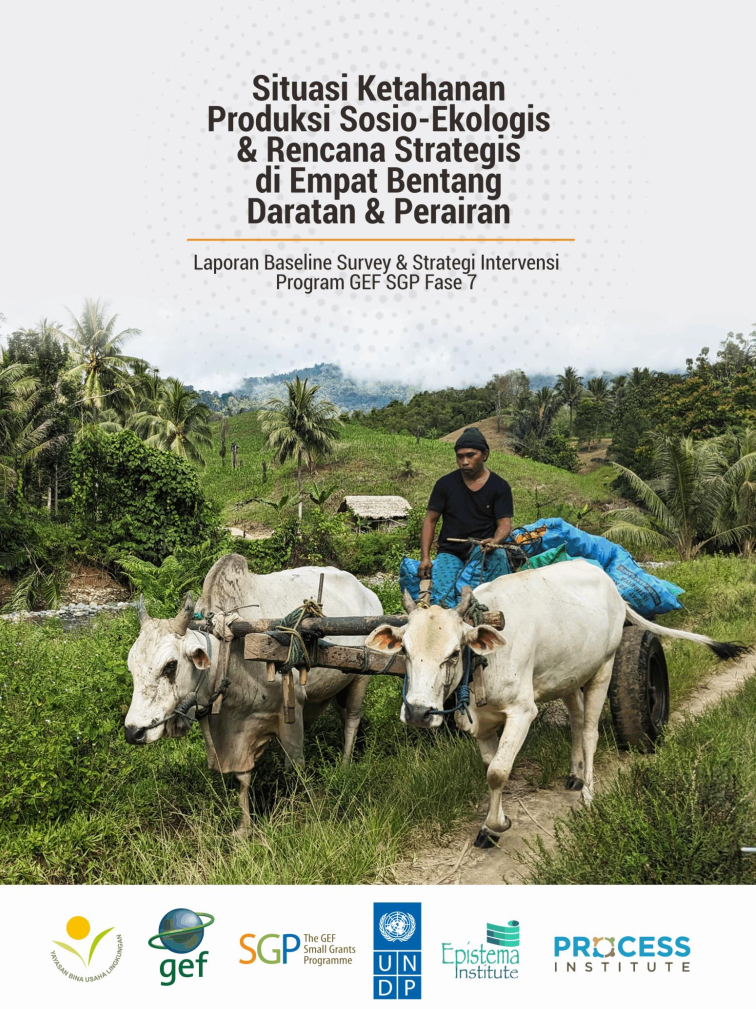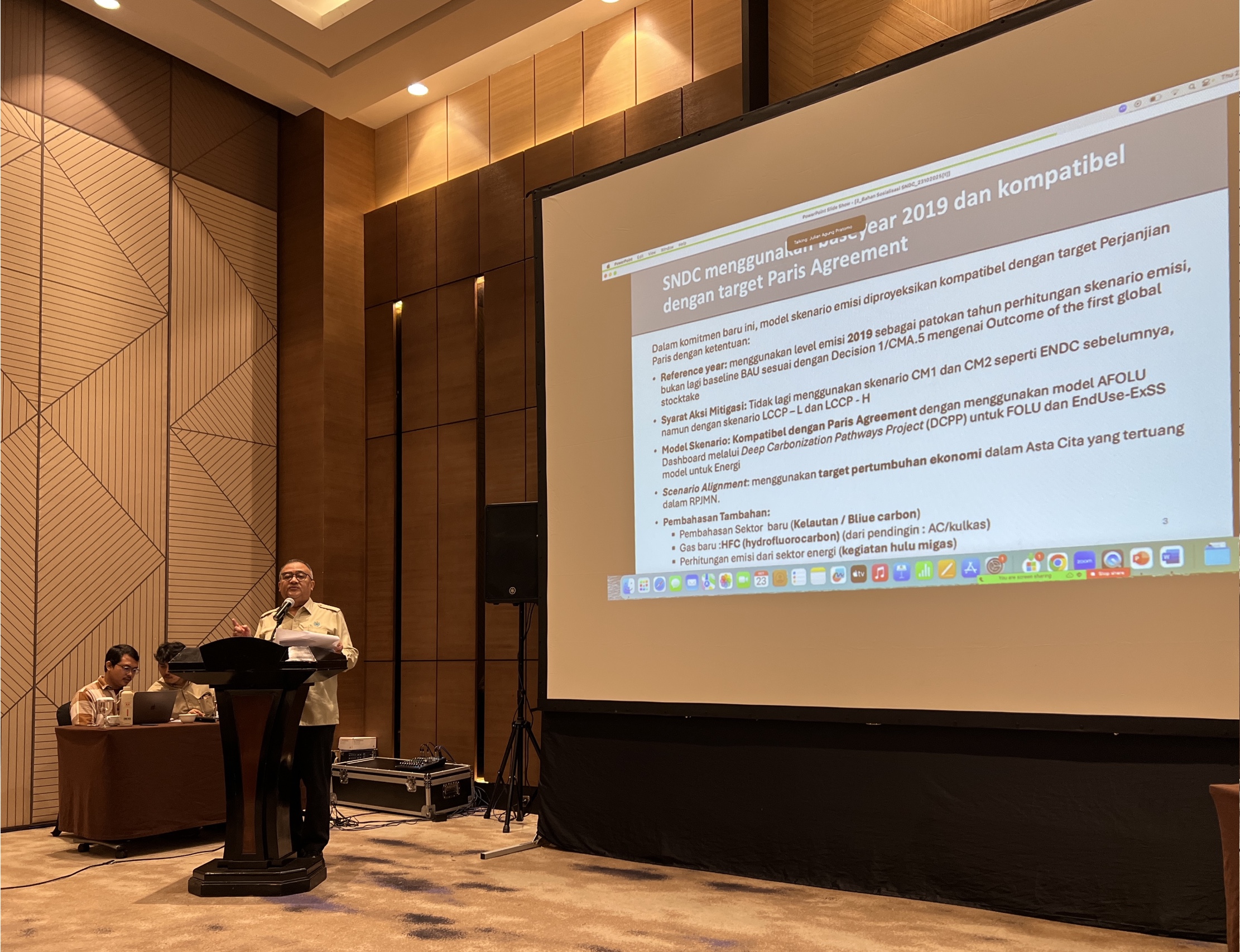Oelbanu, Amfoang Selatan – Kamis pagi (18/9), suara gong pembuka menggema di halaman kantor Desa Oelbanu. Warga sudah menyiapkan meja panjang berisi pangan lokal diantaranya nasi sorgum atau buka, gaplek ubi, bunga pepaya, sambal jantung pisang, sampai kudapan manis berbentuk bola dari jagung yang mereka sebut U’ Anu. Festival Pangan Lokal ini bukan sekadar pesta makan bersama. Ia adalah panggung untuk bercerita bagaimana pangan lokal di Desa menjadi “peluru” ketika badai dan pandemi melanda.
Meriana Bokos, warga Desa Bioba, Amfoang Barat Daya, masih ingat betul bagaimana badai Seroja memporak-porandakan rumah dan ladang. Tapi ia dan keluarganya tetap bisa makan.
“Waktu Seroja itu kami dapat makan dari jagung, pisang, ubi-ubian yang kami tanam. Waktu COVID juga kami tidak susah makan. Kami kesulitan hanya kopi dan gula, karena itu dari luar. Tapi kalau makan yang pokok itu tetap ada,” katanya.
Cerita yang sama datang dari Marci Tanaos, penggiat pangan lokal Desa Oh Aem 1, Amfoang Selatan. Dalam sesi dialog pangan, ia menuturkan bahwa apa yang mereka tanam, membantu mereka menghadapi situasi krisis. “Ubi dan sayur sampai jahe di pekarangan jadi penolong. Itu peluru kami untuk hadapi masa krisis. ” ujar Marci.
Kisah keduanya menjadi pengingat bahwa saat bencana, yang menyelamatkan bukan beras impor, melainkan hasil kebun yang ditanam, disimpan, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pemerintah kecamatan pun mengakui hal itu. Yan Tamoes, PLT Camat Amfoang Selatan, mengatakan festival pangan penting untuk menjaga kebiasaan menanam warga.
“Melalui festival kita kembali mendorong masyarakat untuk terus berbenah diri dan berusaha agar pangan lokal ini jangan sampai pudar atau hilang dari kita,” ujarnya.
Ia sering turun ke desa, mengingatkan masyarakat agar tidak terlena dengan bantuan pemerintah yang cenderung tidak berkelanjutan. “Kalau musim sulit, yang bisa menolong hanyalah hasil kebun sendiri.” tegasnya.
Nusa Tenggara Timur sejatinya tidak miskin pangan. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT (2023) mencatat ada lebih dari 3,6 juta hektare lahan pertanian non-sawah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Lahan luas ini seharusnya bisa menjadi penopang kedaulatan pangan daerah, bukan sekadar terbengkalai karena fokus berlebihan pada monokultur padi. Ironisnya, di tengah potensi yang berlimpah, masyarakat justru semakin terikat pada beras, padahal tanah mereka menyimpan sumber pangan yang jauh lebih beragam. Riset PIKUL (2018) menemukan 36 jenis pangan lokal yang tahan iklim kering, dari sorgum sampai ubi jalar. Enam tahun kemudian, penelitian Ekora NTT (2024) bahkan menemukan 145 jenis pangan lokal hanya di satu desa, Jeo Du’a, Ende. Namun warisan itu pelan-pelan hilang sebab 19 jenis sudah punah, sisanya masih ada di kebun dan hutan tapi jarang dimakan karena pola konsumsi bergeser ke beras.
Ironisnya, negara ikut memperkuat ketergantungan ini. Perpres No. 81 Tahun 2024 bicara soal diversifikasi pangan, tapi di saat yang sama pemerintah tetap menyalurkan beras 10 kilogram untuk 22 juta penerima. Alih-alih mendorong pangan lokal, kebijakan ini justru membuat masyarakat semakin terjebak pada beras. Padahal di Amfoang, ketahanan pangan bukan teori. Ia hadir dalam bentuk sederhana: jagung dan sorgum yang disimpan di rumah bulat, ubi kayu diparut lalu dipanggang jadi laku bika, atau pisang yang diolah menjadi Uki Losi (olahan pisang yang dimasak dengan madu). Semua itu tumbuh di tanah sendiri, tanpa perlu menunggu bantuan dari luar.
Namun iklim yang tak menentu tetap jadi tantangan. “Kalau memang hujan kurang, itu mempengaruhi tanaman baik ubi-ubian bahkan padi jagung. Hasil juga tidak memungkinkan. Tapi sekarang masih gampang ketemu ubi di kebun, bisa simpan, masih ada,” kata Meriana.
Festival pangan di Oelbanu menjadi pengingat bahwa pangan lokal adalah identitas budaya sekaligus benteng desa menghadapi krisis iklim. Bagi warga, ubi, jagung, dan pisang bukan sekadar makanan tapi juga senjata untuk bertahan hidup.
Dari Amfoang, warga belajar bahwa ketahanan tidak datang dari bantuan, tapi dari tanah yang mereka rawat sendiri, dari benih yang ditanam, dan dari keyakinan bahwa pangan lokal bukan sekadar pilihan, melainkan jalan menuju kemandirian.
Sumber :
- Adger, W. N., Huq, S., Brown, K., Conway, D., & Hulme, M. (2003). Adaptation to climate change in the developing world. Progress in Development Studies, 3(3), 179–195. https://doi.org/10.1191/1464993403ps060oa
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT. (2023). Luas penggunaan lahan sawah menurut kabupaten/kota. Kupang: Pemerintah Provinsi NTT.
- Ekora NTT & Yayasan PIKUL. (2024). Proyek pangan nasional di Desa Je’o Du’a: Ancaman perubahan iklim dan runtuhnya kedaulatan pangan. Laporan riset.
- Ratumakin, P., Nomleni, A., & Kuswardono, P. T. (2021). Kajian kebijakan kemandirian pangan lokal di Kabupaten Kupang dan Sabu Raijua. Kupang: Yayasan PIKUL & Yayasan Sheep Indonesia.
- Soro, D., Nomleni, A., & Kuswardono, P. T. (2025). Memo kebijakan: Kedaulatan pangan NTT – Tantangan, potensi, transformasi. Yayasan PIKUL.
- Wawancara dengan Yan Tamoes, Camat Amfoang Selatan, 18 September 2025.
- Wawancara dengan Meriana Bokos, Warga Desa Bioba, 18 September 2025